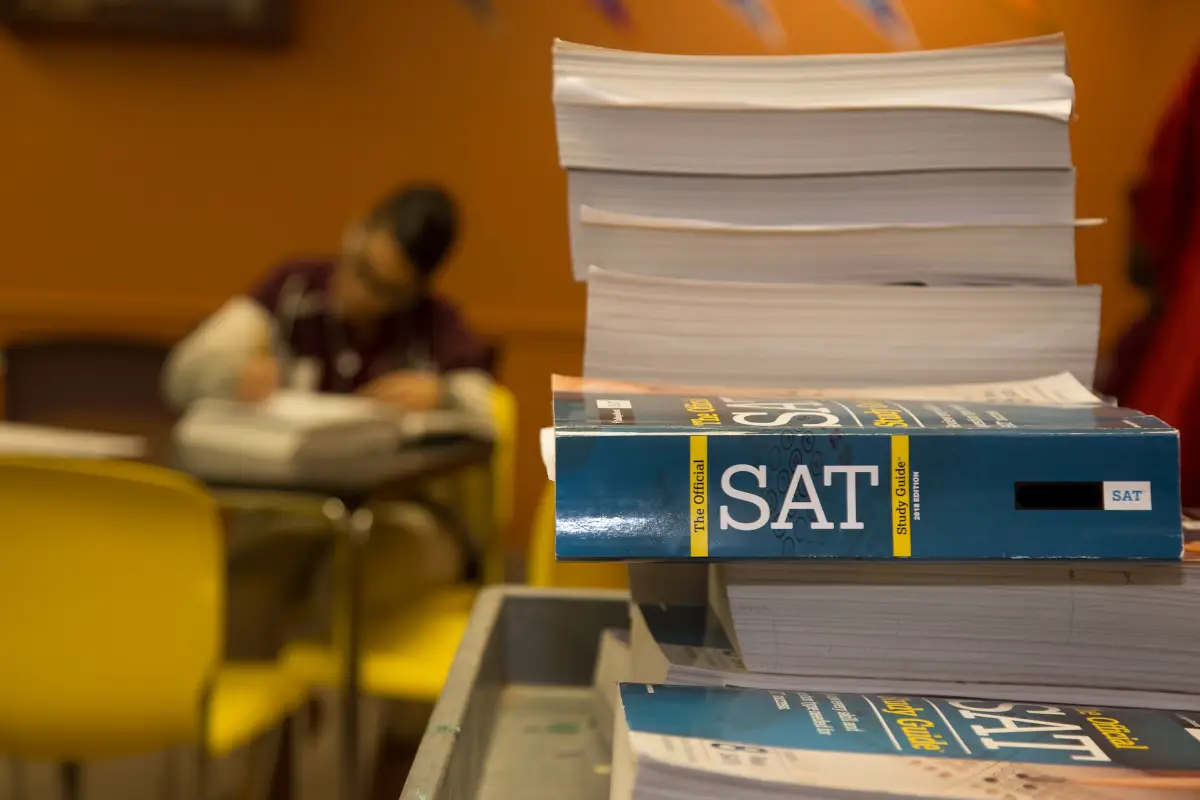Makanan Khas Pare Kediri “Nasi Pecel Tumpang”. Lesehan Pecel Tumpang warung Bu Susie, tongkrongan muda-mudi saat malam di Pare – Kediri.
Malam itu tepat ba’da adzan isya saya datang ke lesehan pecel tumpang Susie yang berada di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Pare. Lesehan itu tampak sederhana sekali. Letaknya berderet dan berjejar dengan warung-warung lain yang juga menawarkan menu santapan khas kaki lima. Tak begitu sulit menemukan warung ini. Bilamana anda warga Pare ataupun pendatang yang baru saja berinjak kaki di Pare, tak tahu-menahu nama jalan, cukuplah mencari tahu atau bertanya di mana keberadaan masjid An-Nur Pare yang berdiri megah itu dengan menaranya yang tinggi putih menjulang ke atas. Nah, kalau sudah ketemu, anda tinggal menelusur ke arah barat. Tengoklah sisi selatan jalan. Lesehan ini berada di deretan pertama (bilamana anda dari arah timur). Dari situ sudah bisa terbaca dengan jelas “Lesehan Susie” yang terpampang di sebuah spanduk kuning tua. Pecel tumpang pincuk – menu utama lesehan ini.
“Bu, Susie…”, sapa saya
“Hey, mari masuk. Sebelah sini lebih enak ngobrolnya”, sambutnya ramah
Saya pun langsung duduk di ujung barat meja. Persis di depan penganan yang tertata rapi dan menggugah lidah untuk mencicip. Memang beberapa hari sebelumnya saya sudah janjian dengan bu Sus untuk wawancara. Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin membuat catatan tentang kuliner Pare dan wilayah sekitarnya; yang sampai hari ini – sepanjang yang saya tahu – belum pernah ada yang menuliskannya sebagai dokumentasi sejarah masa depan. Hal ini pun menjadi ikhtiar awal untuk memulai mengendus dan mendokumentasikan jejak-jejak budaya di Pare yang (mungkin) semakin teraleniasi, masih bertahan, atau bermetamorfosis menjadi budaya baru seiring dengan perubahan yang begitu cepat di masyarakatnya.
Lesehan masih terlihat sepi malam itu. Belum banyak pengunjung yang datang. Hanya beberapa anak muda yang sedang makan nasi pecel dan sekadar nongkrong sambil ngopi dan rokok’an. Seperti biasa setiap kali jualan bu Sus hanya ditemani anaknya; Lulus. Niat hati ingin memesan segelas jahe hangat sebagai teman wawancara, namun belum sempat berucap saya pun langsung disuguhi dengan segelas kopi susu.
“Bu Sus, bisa sampeyan ceritakan awal mulanya jualan nasi pecel tumpang?” tanya saya memulai
“Ya, jadi begini mas, awalnya sebelum saya jualan nasi pecel tumpang, saya jualan sayur. Kemudian sama suami, saya ditawari kamu mau jualan nasi. Saya tanya, jualan dimana? Suami saya menjawab di depan taman makam pahlawan. Seberang rumah sakit Amelia itu. Waktu itu saya berpikir sejenak. Menimbang-nimbang keputusan. Akhirnya, saya setuju untuk jualan di sana.”
“Itu tahun berapa, bu?”
“Saya masih ingat betul pertama kali jualan itu mas, tanggal 2 Agustus 2000” jawab perempuan yang punya nama lengkap Lusi Susanti ini.
“Waktu pertama kali jualan itu bagaimana?”
“Awalnya tidak seperti ini mas. Saya belum jualan banyak seperti ini. Hanya nasi pecel tumpang dan minuman saja. Namanya juga masih babat alas ya mas, pasti ada saja halangannya. Dulu itu waktu saya jualan sering kali dirusuhi. Maksudnya sepulang dari jualan kan segala perabot hanya ditaruh di belakang taman itu, cuma ditutup rapat asal tidak terlihat dari jalan saja. Saya sering kali kecolongan. Mulai gelas, piring, pokok perabot-perabot jualan. Tapi saya biarkan saja. Saya cuma berpikir mungkin ini cobone wong golek rejeki. Ben sing kuoso sing mbales” katanya sambil tersenyum
Tak berapa lama kami mengobrol ada pengunjung yang datang. Dua orang remaja. Mereka memesan nasi pecel tumpang. Bu Sus pun langsung melayani. Terlihat mereka begitu menikmatinya. Sesekali satu di antara remaja itu mengambil bakwan sebagai lauk tambahan. Lulus yang sedari tadi pergi setelah membuatkan saya kopi susu segera kembali. Melaksanakan tugasnya sebagai pembuat minum. Saya pun berhenti sejenak. Menikmati kopi susu yang disuguhkan sedari tadi.
***
Pecel – Tumpang. Dua jenis santapan yang berbeda namun satu keterpaduan dan saling melengkapi. Santapan ini begitu familiar sekali bagi masyarakat Pare. Hampir setiap warung-warung atau lesehan-lesahan yang buka pagi, siang, sore, malam, atau dini hari sekali pun umumnya menyuguhkan santapan ini. Hal ini sudah menjadi budaya bahkan karakter kuliner yang paling sering dinikmati warga. Sederhana. Bercita rasa.
 Belum pernah ada sejarah tertulis – sepanjang yang saya tahu – yang menerangkan dengan jelas asal muasal pecel – tumpang di Pare. Bahkan dalam bukunya Mojokuto, antropolog Amerika Clifford Geertz yang pernah melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa sekira tahun 1960-an di Pare ini tidak menerangkan dengan detil. Yang pasti santapan ini sudah ada sejak nenek saya masih belum menikah(yang kebetulan saya sempat bertanya ke nenek saya). Maka jangan heran bila di setiap sudut Pare mudah sekali ditemui para penjual nasi pecel tumpang.
Belum pernah ada sejarah tertulis – sepanjang yang saya tahu – yang menerangkan dengan jelas asal muasal pecel – tumpang di Pare. Bahkan dalam bukunya Mojokuto, antropolog Amerika Clifford Geertz yang pernah melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa sekira tahun 1960-an di Pare ini tidak menerangkan dengan detil. Yang pasti santapan ini sudah ada sejak nenek saya masih belum menikah(yang kebetulan saya sempat bertanya ke nenek saya). Maka jangan heran bila di setiap sudut Pare mudah sekali ditemui para penjual nasi pecel tumpang.
Tak begitu sulit membuatnya sebab bahan-bahannya sangat merakyat sekali. Jikalau pecel berbahan dasar kacang tanah sedang tumpang lebih ke perpaduan tempe waras dan tempe bosok yang diracik dengan cabe rawit dan cabe besar dengan rempah-rempah lainnya. Namun, cita rasa yang dihasilkan akan berbeda antara satu tangan dengan tangan yang lain. Antara warung lesehan yang satu dengan yang lainnya. Begitulah. Masing-masing akan mempunyai karakter rasa yang khas.
Demikian halnya dengan lesehan Susie. Bilamana anda mampir ke lesehan ini dan mencicip sepincuk nasi pecel tumpang yang disuguhkan, segera anda bisa membedakan karakter rasa pecel tumpangnya dengan warung lesehan lain di Pare. Tidak begitu mahal. Sepincuk nasi pecel tumpang di lesehan ini hanya seharga tiga ribu rupiah.
***
Malam semakin beranjak. Pengunjung pun mulai ramai berdatangan. Bu Sus semakin sibuk melayani. Saya masih belum berpindah tempat duduk. Sembari menulis hal-hal yang kami bicarakan tadi. Dan sesekali meminum kopi susu yang mulai mendingin. Mengeluarkan sebatang rokok lalu menyulutnya.
“Bu Sus, lesehan ini biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa?” tanya saya kembali
“Kalau persiapan itu jam lima sore, mas. Setelah magrib mulai jualan sampai malam jam dua belas.”
“Setiap hari berapa kilo nasi yang dimasak, bu?”
“Tidak pasti. Tapi kalau dirata-rata kurang lebih 10 Kg setiap harinya. Seperti kemaren itu, saya sampai menanak dua kali saking ramenya” jawabnya sambil tersenyum
“Pernah sampai tidak habis bu jualannya?”
“Ya pernah, mas”
“Kalau tidak habis, nasinya itu dibuang atau dibagi-bagikan?”
“Biasanya dibagikan, namun kadang-kadang juga kalau sisa nasinya banyak itu dibuat krupuk puli,mas”
“Kalau kulupan dan lalapannya tidak habis?”
“Kalau itu dibuang, mas. Soalnya kan tidak tahan lama.”
Saya kembali diam sejenak. Menghisab rokok yang tadi sudah tersulut sambil meminum kopi susu yang sudah dingin. Mencatat pembicaraan kami. Namun para pengunjung masih tampak menikmati santapannya sambil mengobrol dengan santai. Sesekali terdengar riuh gelak tawa di antaranya. Saya melihat jam. Sungguh tak terasa sudah hampir jam sepuluh malam. Saya pun bersiap untuk mengakhiri wawancara.
“Selama tujuh tahun jualan nasi pecel tumpang, njenengan punya mimpi atau harapan apa, bu?”
“Maksudnya”
“Maksud saya satu keinginan besar yang mungkin sampai hari ini masih belum terwujud”
“Wah banyak, mas. Kalau adiknya Lulus yang sekarang masih sekolah itu minta ingin dikuliahkan. Ya, mudah-mudahan saya diberi rejeki yang banyak, warungnya lancar dan bisa mengkuliahkan anak saya itu. Lulus sendiri maunya meneruskan jualan ini saja. Dia tidak berminat untuk melanjutkan sekolahnya. Namun, selama ini sejujurnya saya mengidamkan ingin membangun rumah sendiri”
 Saya terkagum mendengar jawaban seorang perempuan sederhana yang sudah berusia kepala empat itu. Di sebalik pekerjaannya sebagai penjual nasi pecel tumpang, serta senyum ramahnya yang membuat pengunjung nyaman, terselip secuil mimpi yang berarti untuk diri dan keluarganya.
Saya terkagum mendengar jawaban seorang perempuan sederhana yang sudah berusia kepala empat itu. Di sebalik pekerjaannya sebagai penjual nasi pecel tumpang, serta senyum ramahnya yang membuat pengunjung nyaman, terselip secuil mimpi yang berarti untuk diri dan keluarganya.
Jam menunjuk pukul setengah sebelas malam. Kopi susu yang sedari tadi mendingin telah habis terminum. Saya pun mengakhiri perbincangan dan berpamitan pulang. Banyak hal yang saya dapat dari obrolan selama empat jam tersebut.
Sekali lagi pecel tumpang tak hanya sebuah santapan pengenyang perut belaka. Ia juga produk budaya yang sayang sekali bila kita biarkan merana. Karena tak ada yang tahu, dua puluh tahun ke depan apakah ia masih menjadi kuliner yang sering dinikmati atau justru semakin tersisih dan langka.
Demikian artikel Lesehan Pecel Tumpang Pare-Kediri dan Secuil Mimpi oleh: Iwan Kapit – Kediri, 2009